Perasaan tertekan sebagai akibat kehidupan di era kolonial ditransformasikan ke dalam bentuk seni pertunjukan. Meski dari awal tayub adalah seni gambyong istana, pada perkembangannya harus keluar menjadi seni rakyat yang makin hari dipandang dari sisi mesumnya, minuman keras, berkualitas rendah, dan bertendensi prostitusi. Paradoks atas kondisi tayub saat ini tidak lepas dari lemahnya kemampuan masyarakat memahami kebudayaan sebagai dasar dalam proses kehidupan.
Tayub adalah kesenian yang mengeksploitasi gerak tari dan suara, seperti halnya cokek yang dikenal dalam kebudayaan masyarakat Betawi. Seni tayub merupakan kesenian turun tumurun dengan iringan gamelan lengkap pelog slendro yang dimainkan nayoko (panjak). Gending-gending yang dinyanyikan para waranggono, di antaranya pangkur, sinom, palaran dan gending dolanan.
Kesenian langen tayub lekat pada keseharian masyarakat Jawa umumnya. Ada keyakinan yang bersifat mistik bahwa manusia bisa mempengaruhi kesuburan tanah dan tanaman dengan melakukan gerak tari yang memperlihatkan hubungan antara pria yang disimbolkan sebagai benih tanaman, dan wanita sebagai simbol sawah atau ladang.
Kesenian ini nyaris mulai termarginalkan keberadaannya sebagai warisan budaya (cultural heritage), akan tetapi masih eksis, tumbuh dan berkembang di daerah Tuban dan Nganjuk. Selain itu dapat kita temui misalnya di Bojonegoro, sisi selatan dari Lamongan, Surabaya, Tulungagung, Madiun dan pinggiran Kabupaten Pasuruan sampai Malang. Kesenian tayub dilakukan pada momen-momen tertentu seperti sedekah bumi, sunatan, pernikahan, ritual tradisional, sadranan, memasuki musim tanam, hingga peringatan hari besar nasional.
Tayub sebagai ditata ben guyub (diatur agar tercipta kerukunan), sebuah filosofi yang ditanamkan pada tayub sebagai kesenian untuk pergaulan. Nilai dasarnya adalah kesamaan kepentingan untuk mengapresiasikan kemampuan, jiwa, seni dan talenta, baik kemampuan sebagai penabuh gamelan (pengrawit) ataupun penarinya. Kesamaan ini akan melahirkan keselaras-serasian tayub sebagai suatu bentuk tarian hentakan kaki yang sesuai dengan bunyi kendang, lambaian tangan seirama gambang, atau lenggok kepala pada tiap pukulan gongnya.
Profesi Waranggono
Para wanita penari tayub dulunya disebut sindir. Agar terkesan lebih halus, saat ini disebut waranggono. Untuk setiap satu pertunjukan, mereka biasanya bisa menggaet uang Rp 300 ribu hingga Rp 700 ribu. Penghasilan tersebut didapat sampai rata-rata empat sampai lima kali sebulan. Dengan penghasilan sebesar tadi, para waranggono bisa dibilang hidup berkecukupan.
Akan tetapi menjadi penari tayub (waranggono) tak semudah yang dibayangkan orang awam. Berbagai ritual supranatural dan pilihan-pilihan rumit dihadapkan pada waranggono. Mereka kerap disodori minuman keras oleh para tamu. Hal itu menjadikannya serba salah, dan jika diterima dan meminumnya, maka akan berpengaruh pada kesadaran dan kualitas suaranya, yang sekaligus membuatnya tidak bisa seutuhnya melakoni peran itu. Sebaliknya, jika ditolak, akan memancing kemarahan sang tamu. Bahkan tak jarang mereka mendapat perlakuan kasar karena dinilai tidak berlaku sopan terhadap tamu.
Mereka juga harus dihadapkan pada ritual supranatural yang sulit seperti ritual Gembayangan. Masyarakat setempat menyebutnya "wisuda waranggono". Acara yang bermakna serupa dengan pemberiaan lisensi ini dilaksanakan setiap Jumat Pahing, bulan Dzulhijah, atau biasa disebut Bulan Besar dalam penanggalan Jawa.
Tahap pertama prosesi ini adalah amek tirto atau pengambilan air suci di Air Terjun Sedudo, sekitar 30 kilometer arah selatan Ngrajek. Untuk boleh menjalani tahap ini, para calon waranggono harus mampu menari minimal 10 gending tarian. Pada tahapan ini, mereka dipapah menemui Juru Kunci Sedudo untuk menyerahkan sesajen sekaligus meminta restu.
Setelah restu diyakini sudah didapat, mereka harus menari di dalam air terjun berketinggian 137 meter sebagai tanda penghormatan. Kemudian, barulah pengambilan air suci dilaksanakan melalui perantara Sedudo. Selanjutnya, air yang telah dimasukkan ke dalam wadah yang disebut klenteng tadi diserahkan kepada sesepuh seni tayub untuk dipercikkan ke kepala mereka. Sejak saat itu, para gadis tadi resmi menjadi waranggono.
Image Negatif
Dalam Serat Centhini, yang penulisannya diprakarsai Paku Buwono V, disebutkan bahwa tayub selalu identik dengan prostitusi karena fungsi waranggana atau tledhek memang sebagai penghibur laki-laki. Cerita yang biasa beredar di arena pentas tayub, para waranggana bisa dibooking (berkencan) di luar pentas., banyak tledhek menjadi kekasih gelap penggemarnya. Bahkan tak sedikit dari mereka dinikahi oleh pengusaha atau pejabat.
Faktor lain penyebab terus menurunnya popularitas tayub adalah keberadaan sindir yang sering diidentikkan dengan wanita penggoda. Sterotip negatif ini sering dijadikan alasan untuk mendeskreditkan para sindir, sehingga kian dijauhi oleh penggemarnya. Alasan seperti itu sebenarnya tidak mengandung kebenaran kalau dibandingkan dengan goyangan penyanyi dangdut saat ini.
Alasan dosa merupakan dogma dan titik mati atas suatu aksi atau gerak. Hal ini didasarkan pemahaman akan teks dan konteks agama. Akibatnya, seperti tidak ada kebenaran pada setiap gerak yang mengandung dosa. Dalam tayub, gerak dan aksi itu, adalah suwelan dan mabuk-mabukan. Hakikat suwelan adalah pemberian uang kepada waranggana oleh seseorang setelah ngibing. Ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kesempatan untuk ngibing bersamanya. Cara pemberian suwelan biasanya diselipkan pada belahan payudara waranggana. Bisa pada bagian luar atau juga ada yang diselipkan lebih dalam lagi pada sisi-sisi payudara. Kedua, dengan minum alkohol tadi diharapkan bisa membantu sugesti dan kepercayaan diri seseorang untuk ngibing bersama penari tayub.
Konteks kesenian pedesaan seperti tayub memiliki hakikat sebagai ekspresi dan semangat untuk dekat dengan kepercayaannya. Maka seyogianya, pendekatan awal yang digunakan ada pada sisi akidah (teologi). Biarkan seni tayub berkembang, ambil positifnya lalu masuki dan arahkan.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)















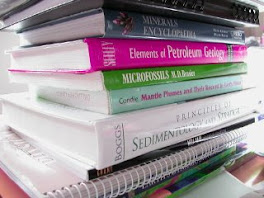

Tidak ada komentar:
Posting Komentar