
MENGUNGKAP POLITIK KEBUDAYAAN KAUM BERSARUNG
Judul Buku : Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan
Penulis : Choirotun Chisaan
Penerbit : LKiS
Cetakan : I, Maret 2008
Tebal : V+247 Halaman
Peresensi : Iqro' Alfirdaus
Pada masa “Demokrasi Terpimpin” lembaga seni budaya banyak yang berafiliasi dengan partai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa seni budaya telah dimanfaatkan secara ekstensif sebagai alat tindakan politik. Hampir dapat dipastikan partai politik yang berbasis massa besar hingga yang terkecil memiliki lembaga seni budayanya masing-masing. Yang pada pempublikasiannya, akhirnya memicu timbulnya polemik dalam domain kebudayaan. Polemik tersebut berawal dari persoalan ‘Timur dan Barat’ (1930-an) sebelum terbentuknya lembaga kesenian dan kebudayaan, yang mengkerucut pada persoalan ‘Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan Dunia’ (1950-an), dan ‘Politik Aliran Kebudayaan’ (1960-an) setelah lembaga kesenian dan kebudayaan terbentuk.
Buku yang berjudul Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan yang di tulis oleh Choirotun Chisaan ini hendak mengungkap sisi lain NU yang selama ini diidentikkan dengan organisasi kaum bersarung sebagai partai politik Islam dalam pergaulannya, yang juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Indonesia demi menjawab segala tantangan modernitas yang terjadi pada saat itu dengan lembaga keseniannya Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia).
Indonesia yang berada dalam proses pembentukan negara-bangsa menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang memerlukan pembenahan dalam berbagai sektor kehidupan. NU mempunyai badan otonom yang mencerminkan perhatiannya pada masalah pendidikan, sosial, dakwah, perempuan, pemuda, dan buruh. Dalam perkembangan selanjutnya, bagian-bagian dan badan-badan yang otonom yang ada di tubuh NU semakin bertambah seiring meluasnya perhatian pada masalah lain. Termasuk Lesbumi yang dibentuk pada tahun 1962 yang berkonsentrasi pada seni budaya.
Ada dua faktor yang mendorong lahirnya Lesbumi. Pertama adalah faktor ekstern, yang meliputi; dikeluarkannya Manifesto Politik pada tahun 1959, pengarusutamaan Nasakom dalam tata kehidupan sosio-budaya dan politik Indonesia pada tahun 1960-an, dan perkembangan Lekra (1950), organisasi kebudayaan yang sejak akhir tahun 1950-an dan seterusnya semakin menampakkan kedekatan hubungan dengan PKI baik secara kelembagaan maupun ideologis. Kedua, adalah faktor intern yakni, kebutuhan pendampingan terhadap kelompok-kelompok seni budaya di lingkungan nahdiyyin, dan kebutuhan akan modernisasi seni budaya.
Lesbumi adalah merupakan reaksi terhadap perkembangan Lekra, karena kemunculannya baru pada tahun 1962, dua belas tahun setelah kelahiran Lekra. Akan tetapi, kelahiran Lesbumi dalam konteks politik kebudayaan merupakan satu kemestian, satu conditio sine qua non atas jalannya revolusi Indonesia yang menganut gagasan Nasakom Soekarno. Kemestian inilah yang menegaskan kehadiran Lesbumi bukan untuk mendirikan organisasi kebudayaan. Kehadiran Lesbumi juga merupakan reaksi terhadap berbagai macam tantangan yang datang dari berbagai arah yang mengitari kaum muslimin.
Lesbumi membawa warna yang berbeda dari Lekra. Lesbumi membawa genre “religius”. Ia merupakan manifestasi dari cita-cita dan gagasan kesatuan Nasakom Soekarno yang meniscayakan terhadap agama sebagai unsur mutlak dalam nation and character building di bidang kebudayaan. Pendefinisian ini sejalan dengan tujuan revolusi Indonesia yang menginginkan tercapainya masyarakat yang adil makmur lahir batin yang diridlai Allah. Diyakini bahwa jalannya revolusi Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Politik, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam kesatuan Pancasila sebagai landasan ideal.
Sehubungan dengan itu, penegasan Soekarno bahwa pancasila adalah satu hogere optreking dari pada Deklartion of Independence (yang tidak membawa keadilan sosial bagi sosialisme) dan Manifesto Komunis (yang harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa) memunculkan acuan penting mengenai sosialisme yang bertaut dengan religiusitas di dalam praktik kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Humanisme religius adalah istilah yang muncul sebagai turunan. Yang dalam konteks Lesbumi, religiusitas menjadi tendensi, bukan hanya dalam ekspresi dan produksi seni budayanya, melainkan juga aktivis-aktivis yang menggerakkannya seperti yang dikemukakan oleh tiga tokohnya, Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani.
Lesbumi dengan semboyan Humanisme religius-nya juga memberikan alternatif baru dalam polemik dalam mementukan arah kebudayaan yang terjadi antara Lekra yang beraliran realisme sosialis dan Manifes Kebudayaan yang beraliran humanisme universal. Lesbumi menolak jargon “politik adalah panglima” yang menjadi motor penggerak aktivitas Lekra, dan semboyan “seni untuk seni” (l’ art pour l’ art) yang menjadi elan vital Manifes Kebudayaan.
Oleh karena itu, buku ini sangat menarik sebab memaparkan upaya NU mencari relasi antara agama, seni, dan politik hingga Lesbumi resmi dibentuk. Sebagai organisasi kebudayaan di bawah naungan NU, Lesbumi telah melakukan kopromi politik dan agama dalam konteks “kemusliman” melalui pendefinisian kebudayaan “Islam”. Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini merupakan wujud dari respon NU terhadap modernitas. Dari buku ini kita dapat melihat bahwa NU sebagai ormas tidak hanya berkecimpung dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan, tetapi juga kebudayaan.
Lesbumi meski secara kelembagaan telah hilang namun, sebagai lembaga kesenian dan kebudayaan yang berada di bawah naungan NU, ia telah memberi sumbangan besar terhadap tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Indonesia terkubur dalam ingatan yang terlupakan. Kehadiran buku ini sangat pantas untuk dibaca oleh berbagai kalangan terutama pengamat sejarah, politik, dan kebudayaan. Karena selama ini dalam perbincangan sejarah, politik, dan kebudayaan Lesbumi kurang disinggung kalau tidak mau dikatakan teracuhkan peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah seni dan kebudayaan Indonesia.
Penulis : Choirotun Chisaan
Penerbit : LKiS
Cetakan : I, Maret 2008
Tebal : V+247 Halaman
Peresensi : Iqro' Alfirdaus
Pada masa “Demokrasi Terpimpin” lembaga seni budaya banyak yang berafiliasi dengan partai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa seni budaya telah dimanfaatkan secara ekstensif sebagai alat tindakan politik. Hampir dapat dipastikan partai politik yang berbasis massa besar hingga yang terkecil memiliki lembaga seni budayanya masing-masing. Yang pada pempublikasiannya, akhirnya memicu timbulnya polemik dalam domain kebudayaan. Polemik tersebut berawal dari persoalan ‘Timur dan Barat’ (1930-an) sebelum terbentuknya lembaga kesenian dan kebudayaan, yang mengkerucut pada persoalan ‘Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan Dunia’ (1950-an), dan ‘Politik Aliran Kebudayaan’ (1960-an) setelah lembaga kesenian dan kebudayaan terbentuk.
Buku yang berjudul Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan yang di tulis oleh Choirotun Chisaan ini hendak mengungkap sisi lain NU yang selama ini diidentikkan dengan organisasi kaum bersarung sebagai partai politik Islam dalam pergaulannya, yang juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Indonesia demi menjawab segala tantangan modernitas yang terjadi pada saat itu dengan lembaga keseniannya Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia).
Indonesia yang berada dalam proses pembentukan negara-bangsa menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang memerlukan pembenahan dalam berbagai sektor kehidupan. NU mempunyai badan otonom yang mencerminkan perhatiannya pada masalah pendidikan, sosial, dakwah, perempuan, pemuda, dan buruh. Dalam perkembangan selanjutnya, bagian-bagian dan badan-badan yang otonom yang ada di tubuh NU semakin bertambah seiring meluasnya perhatian pada masalah lain. Termasuk Lesbumi yang dibentuk pada tahun 1962 yang berkonsentrasi pada seni budaya.
Ada dua faktor yang mendorong lahirnya Lesbumi. Pertama adalah faktor ekstern, yang meliputi; dikeluarkannya Manifesto Politik pada tahun 1959, pengarusutamaan Nasakom dalam tata kehidupan sosio-budaya dan politik Indonesia pada tahun 1960-an, dan perkembangan Lekra (1950), organisasi kebudayaan yang sejak akhir tahun 1950-an dan seterusnya semakin menampakkan kedekatan hubungan dengan PKI baik secara kelembagaan maupun ideologis. Kedua, adalah faktor intern yakni, kebutuhan pendampingan terhadap kelompok-kelompok seni budaya di lingkungan nahdiyyin, dan kebutuhan akan modernisasi seni budaya.
Lesbumi adalah merupakan reaksi terhadap perkembangan Lekra, karena kemunculannya baru pada tahun 1962, dua belas tahun setelah kelahiran Lekra. Akan tetapi, kelahiran Lesbumi dalam konteks politik kebudayaan merupakan satu kemestian, satu conditio sine qua non atas jalannya revolusi Indonesia yang menganut gagasan Nasakom Soekarno. Kemestian inilah yang menegaskan kehadiran Lesbumi bukan untuk mendirikan organisasi kebudayaan. Kehadiran Lesbumi juga merupakan reaksi terhadap berbagai macam tantangan yang datang dari berbagai arah yang mengitari kaum muslimin.
Lesbumi membawa warna yang berbeda dari Lekra. Lesbumi membawa genre “religius”. Ia merupakan manifestasi dari cita-cita dan gagasan kesatuan Nasakom Soekarno yang meniscayakan terhadap agama sebagai unsur mutlak dalam nation and character building di bidang kebudayaan. Pendefinisian ini sejalan dengan tujuan revolusi Indonesia yang menginginkan tercapainya masyarakat yang adil makmur lahir batin yang diridlai Allah. Diyakini bahwa jalannya revolusi Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Politik, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam kesatuan Pancasila sebagai landasan ideal.
Sehubungan dengan itu, penegasan Soekarno bahwa pancasila adalah satu hogere optreking dari pada Deklartion of Independence (yang tidak membawa keadilan sosial bagi sosialisme) dan Manifesto Komunis (yang harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa) memunculkan acuan penting mengenai sosialisme yang bertaut dengan religiusitas di dalam praktik kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Humanisme religius adalah istilah yang muncul sebagai turunan. Yang dalam konteks Lesbumi, religiusitas menjadi tendensi, bukan hanya dalam ekspresi dan produksi seni budayanya, melainkan juga aktivis-aktivis yang menggerakkannya seperti yang dikemukakan oleh tiga tokohnya, Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani.
Lesbumi dengan semboyan Humanisme religius-nya juga memberikan alternatif baru dalam polemik dalam mementukan arah kebudayaan yang terjadi antara Lekra yang beraliran realisme sosialis dan Manifes Kebudayaan yang beraliran humanisme universal. Lesbumi menolak jargon “politik adalah panglima” yang menjadi motor penggerak aktivitas Lekra, dan semboyan “seni untuk seni” (l’ art pour l’ art) yang menjadi elan vital Manifes Kebudayaan.
Oleh karena itu, buku ini sangat menarik sebab memaparkan upaya NU mencari relasi antara agama, seni, dan politik hingga Lesbumi resmi dibentuk. Sebagai organisasi kebudayaan di bawah naungan NU, Lesbumi telah melakukan kopromi politik dan agama dalam konteks “kemusliman” melalui pendefinisian kebudayaan “Islam”. Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini merupakan wujud dari respon NU terhadap modernitas. Dari buku ini kita dapat melihat bahwa NU sebagai ormas tidak hanya berkecimpung dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan, tetapi juga kebudayaan.
Lesbumi meski secara kelembagaan telah hilang namun, sebagai lembaga kesenian dan kebudayaan yang berada di bawah naungan NU, ia telah memberi sumbangan besar terhadap tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Indonesia terkubur dalam ingatan yang terlupakan. Kehadiran buku ini sangat pantas untuk dibaca oleh berbagai kalangan terutama pengamat sejarah, politik, dan kebudayaan. Karena selama ini dalam perbincangan sejarah, politik, dan kebudayaan Lesbumi kurang disinggung kalau tidak mau dikatakan teracuhkan peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah seni dan kebudayaan Indonesia.















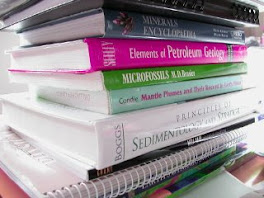

Tidak ada komentar:
Posting Komentar